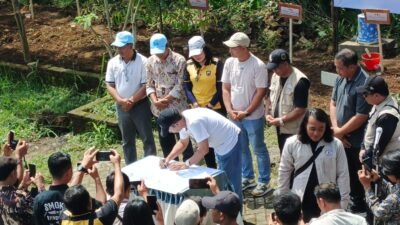Oleh : Dr.(c) Rani Purwanti Kemalasari SH.MH. (Peneliti dalam bidang hukum tata negara)
===========
Intimate.co.id -| Jakarta – Wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD kembali memanaskan panggung politik nasional, dengan pemerintah menekankan efisiensi biaya dan pengurangan praktik politik uang, sementara oposisi dan aktivis demokrasi menudingnya sebagai pintu masuk oligarki politik yang mengikis hak rakyat memilih secara langsung. Di tengah kontroversi ini, Pilkada langsung tetap dipertahankan oleh partai oposisi dan aktivis sebagai penjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sedangkan pendukung Pilkada DPRD, termasuk Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, dan Demokrat, menyoroti keuntungan praktis seperti penghematan anggaran dan kelancaran koordinasi politik. Pertarungan antara dua model ini bukan sekadar soal prosedur, tetapi menjadi ujian nyata bagi keberlangsungan demokrasi substantif di Indonesia.
Polemik ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah efisiensi sebanding dengan berkurangnya kedaulatan rakyat? mari kita melihatnya dari sisi pro dan kontra.
Pro Pilkada Melalui DPRD.
Pilkada Via DPRD mencerminkan Sila ke 4 Pancasila.
Pilkada melalui DPRD sering diperdebatkan kesesuaiannya dengan Sila ke-4 Pancasila, yang berbunyi: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Argumen pendukung pilkada oleh DPRD menekankan pada prinsip demokrasi perwakilan, di mana wakil rakyat (DPRD) dianggap lebih bijaksana dalam memutuskan, selaras dengan “permusyawaratan/perwakilan”. Pendukung pilkada via DPRD berargumen bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi perwakilan. Mereka meyakini keputusan yang diambil melalui musyawarah di lembaga perwakilan (DPRD) lebih mencerminkan “hikmat kebijaksanaan” dibandingkan pilkada langsung.
Pilkada Melalui DPRD sah secara konstitusional.
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Rumusan norma tersebut bersifat terbuka (open legal policy), karena tidak secara eksplisit menentukan metode pemilihan, baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui mekanisme perwakilan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, frasa “dipilih secara demokratis” memberikan ruang tafsir yang sah secara konstitusional kepada pembentuk undang-undang(legislator) untuk menetapkan model pemilihan kepala daerah, sepanjang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.
Money Politics dalam Pilkada : Kesenjangan Antara Norma Hukum dan Penegakan.
Demokrasi pada hakikatnya mensyaratkan legitimasi dan bertujuan untuk mempertinggi kedaulatan rakyat. Namun, praktik pilkada langsung selama ini cenderung hanya merepresentasikan demokrasi prosedural tanpa menjamin demokrasi substantif. Hal ini terutama disebabkan maraknya politik uang (money politics) yang secara nyata mereduksi kebebasan memilih, mengaburkan kehendak rakyat, dan menggeser pertimbangan rasional pemilih ke arah insentif material jangka pendek. Faktor ekonomi masyarakat yang masih rentan semakin memperkuat efektivitas politik uang, sehingga pemilih mudah dipengaruhi oleh hadiah atau materi kampanye. Akibatnya, kedaulatan rakyat yang seharusnya diwujudkan secara substantif menjadi tereduksi; legitimasi kepala daerah yang dihasilkan bersifat semu karena pilihan politik tidak lagi didasarkan pada kapasitas, program, atau visi calon, melainkan pada transaksi ekonomi.
Padahal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara normatif telah mengatur larangan praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Larangan tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 73, yang menegaskan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, disertai dengan ancaman sanksi administratif dan pidana.
Namun demikian, dalam praktik, politik uang dalam pilkada langsung tetap berlangsung secara masif dan sistemik. Hal ini disebabkan salah satunya oleh konstruksi norma Pasal 73 yang mensyaratkan adanya pembuktian melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum sanksi administratif berupa pembatalan pencalonan dapat dijatuhkan. Persyaratan tersebut menempatkan beban pembuktian yang tinggi dan prosedur yang panjang, sehingga penegakan hukum politik uang menjadi tidak efektif dan kehilangan daya cegah (deterrent effect).
Besarnya anggaran dalam Pilkada Langsung.
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menyerap anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Data realisasi anggaran menunjukkan bahwa total belanja Pilkada serentak 2023–2024 mencapai sekitar Rp34,6. Realisasi ini mencapai sekitar Rp34,57 triliun hingga Agustus 2024 dan diperkirakan hampir memenuhi pagu yang ditetapkan Rp37,52 triliun.Besarnya anggaran ini mencakup berbagai komponen pokok penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, di dalamnya juga terdapat kebutuhan biaya pemungutan suara ulang (PSU) yang diperkirakan mencapai hampir Rp1 triliun pada Pilkada 2024. Besarnya beban anggaran yang harus ditanggung oleh negara sering menimbulkan perdebatan mengenai efisiensi penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal publik dan sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah tersebut seyogianya dievaluasi secara cermat melalui prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam undang‑undang tentang keuangan negara dan perencanaan anggaran.
Kontra Pilkada Via DPRD
Terbelenggunya Partisipasi Publik
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama.” Prinsip ini tidak hanya menekankan kesetaraan warga negara di hadapan hukum, tetapi juga menegaskan hak konstitusional mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan, termasuk melalui pemilihan kepala daerah.
Jika pemilihan kepala daerah dialihkan ke DPRD, partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya akan berkurang secara signifikan. Warga hanya berperan secara tidak langsung melalui wakil rakyat, sehingga hak konstitusional mereka untuk ikut serta dalam proses politik menjadi terbatas. Mekanisme ini juga berisiko mengurangi transparansi dan akuntabilitas, membuka peluang politik transaksional, lobbying internal partai, atau intervensi kepentingan elite politik. Dengan demikian, meskipun Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 memungkinkan pemilihan melalui DPRD, dari perspektif Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 mekanisme tersebut berpotensi melemahkan demokrasi partisipatif dan kedaulatan rakyat.
Rawan politik transaksional, oligarki dan melemahkan legitimasi kepala daerah.
Pemilihan kepala daerah melalui DPRD sangat rawan terhadap praktik politik transaksional dan menguatnya oligarki kekuasaan. Proses yang berlangsung di ruang tertutup membuka peluang terjadinya lobi politik, mahar pencalonan, serta barter kepentingan antar elite partai dan anggota DPRD. Dalam situasi seperti ini, keputusan politik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kualitas, kapasitas, dan visi calon, melainkan oleh kekuatan modal, jaringan, serta kompromi kepentingan di antara kelompok elite. Akibatnya, kekuasaan berpotensi terkonsentrasi pada segelintir aktor politik dan ekonomi, sementara aspirasi rakyat tersisih dari proses pengambilan keputusan yang seharusnya mencerminkan kehendak publik.
Selain itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi melemahkan legitimasi kepala daerah di mata masyarakat. Kepala daerah yang terpilih tidak memperoleh mandat langsung dari rakyat, melainkan dari perwakilan politik di lembaga legislatif, sehingga mudah dipersepsikan sebagai “produk elite”, bukan hasil pilihan demokratis warga. Kondisi ini dapat menimbulkan jarak psikologis dan politik antara pemimpin daerah dan masyarakat yang dipimpinnya, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Lemahnya legitimasi moral dan politik tersebut pada akhirnya dapat berimplikasi pada rendahnya dukungan sosial, rapuhnya stabilitas pemerintahan, dan berkurangnya efektivitas kepemimpinan dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
Putusan Mahkamah konstitusi terkait tafsir pemilihan yang demokratis.
MK memang telah menegaskan prinsip demokrasi langsung yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil…” (Luber Jurdil). Norma ini sering dijadikan rujukan dalam putusan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan wajib memenuhi asas tersebut sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Beberapa putusan MK yang menegaskan pengamalan asas Luber Jurdil dalam praktik pemilihan, termasuk di konteks pilkada dan pemilu, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU XX/2022, yang menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian integral dari rezim Pemilihan Umum (Pemilu) dan karena itu wajib dilaksanakan berdasarkan asas Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Putusan ini menguatkan posisi Pilkada sebagai kontestasi yang harus memenuhi prinsip demokrasi langsung oleh rakyat. kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU XXII/2024 juga memperkuat dalil bahwa Pilkada harus berdasarkan prinsip Luber Jurdil dan menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh dikurangi melalui prosedur yang membatasi partisipasi langsung warga negara dalam pemilihan. Putusan putusan ini memperkuat tafsir bahwa asas demokrasi langsung sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bukan hanya norma tekstual tetapi merupakan standar konstitusional yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan, termasuk pilkada.
Dalam konteks demokrasi substantif, bagaimana model Pilkada yang paling tepat diterapkan di Indonesia?
Tidak ada sistem pemilu yang sempurna, sehingga setiap mekanisme penyelenggaraan Pilkada layak untuk dievaluasi secara berkala. Persoalan utama bukan terletak pada sah atau tidaknya suatu mekanisme, melainkan pada penentuan model yang paling tepat untuk diterapkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan rakyat.
Sebenarnya, Pilkada langsung sudah dapat dianggap sebagai mekanisme yang ideal bagi Indonesia, karena selaras dengan semangat reformasi yang menekankan kedaulatan rakyat, partisipasi publik, dan transparansi politik. Sistem ini memungkinkan masyarakat secara langsung memilih pemimpin daerahnya, sehingga aspirasi publik terwujud secara nyata dan akuntabilitas kepala daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Namun, pengalaman empiris selama masa reformasi menunjukkan bahwa Pilkada langsung juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya biaya penyelenggaraan, praktik politik uang yang massif, dan lemahnya penegakan hukum.
Dalam konteks tersebut, Pilkada melalui DPRD dapat dipertimbangkan sebagai alternatif yang menanggapi permasalahan empiris tersebut, dengan catatan mekanismenya dirancang sedemikian rupa sehingga tetap menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan partisipasi publik.
Untuk memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan, proses seleksi calon dan pengambilan keputusan di DPRD perlu disertai mekanisme konsultasi publik, forum musyawarah warga, serta transparansi setiap tahapannya, sesuai dengan prinsip Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta berhak berperan serta dalam proses politik secara nyata.
Agar mekanisme Pilkada DPRD tetap sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, diperlukan reformasi mendalam untuk mencegah dominasi elit politik. Salah satu langkah penting adalah pemberlakuan recall dan sanksi tegas bagi anggota DPRD yang mengabaikan aspirasi rakyat atau terbukti menerima suap. Transparansi juga harus dijamin, dengan kewajiban anggota DPRD mengumumkan calon yang akan dipilih beserta alasan pertimbangannya kepada konstituen sebelum pemungutan suara. Proses uji publik dan fit and proper test terbuka wajib dilakukan sebelum calon diajukan, memastikan kandidat yang muncul merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat, bukan keputusan elit partai semata. Mekanisme ini diperkuat dengan hak konstituen untuk menarik (recall) melalui partai politik kepada anggota DPRD yang membelot dari suara rakyat, sementara integritas partai politik juga harus dijaga melalui sistem rekrutmen calon yang demokratis dan transparan.
Akhirnya, pengawasan publik maksimal melalui keterlibatan LSM, media, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memantau seluruh proses, mencegah praktik politik uang, dan menjaga akuntabilitas sehingga demokrasi substantif tetap terjaga meskipun pemungutan suara dilakukan oleh wakil rakyat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan suatu sistem Pilkada tidak terletak pada apakah ia dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan, melainkan pada sejauh mana proses tersebut benar-benar mampu mewujudkan kedaulatan rakyat, keadilan politik, dan kepemimpinan yang berintegritas. Demokrasi substantif menuntut bukan hanya prosedur yang sah, tetapi juga etika kekuasaan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik; karena itu, setiap pilihan sistem harus senantiasa diarahkan untuk memperkuat, bukan mereduksi makna kedaulatan rakyat dalam praktik bernegara.
Penulis: Kelana Peterson
Kontributor: Intimate.co.id